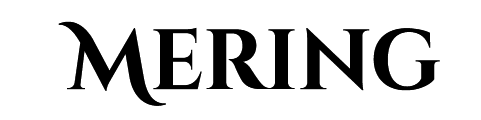Preambul Republik Kelamin: Puisi Hibrida Wisnu Pamungkas yang Menyalak
Bahwa sesungguhnya berpuisi itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan literasi dan akal sehat di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikesusastraan dan perikeadilan. Dan aku menulis buku ini karena ada sesuatu yang membusuk di kepala bangsa, dan aku tidak tahan mencium baunya sendirian saja. Republik Kelamin lahir dari rasa mual yang panjang, mual melihat kepalsuan menjadi iklan akademika, mual mendengar doa dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan, mual menyaksikan paling tidak 5 tahun sekali rakyat dijadikan pemuas syahwat politik penguasa.
Seharusnya aku percaya
bahwa puisi itu lembut, manis, dan berbunga-bunga, tetapi brutalnya kekuasaan
di negeri ini membuat setiap puisi yang kutulis ingin meledak, menjadi amuk jiwa.
Barangkali sebagian orang akan marah setelah
membaca buku ini. Tak apa. Kemarahan adalah tanda masih ada denyut nadi di nadi
kita. Lagi pula aku menulis puisi ini bukan untuk memuaskan sesiapa. Aku
menulis untuk menampar diri sendiri dan siapa pun yang merasa nyaman hidup
dalam kebohongan yang rapi dan sudah begitu akut.
Ketika menulis
puisi-puisi ini, aku sering merasa seperti tengah menggali liang kubur di sebuah
kota. Setiap kata adalah cangkul yang menyingkap bau busuk sejarah. Dari sejak
aku mulai mengingat dunia sampai tahun 2025, tak banyak yang berubah di republik
ini. Buktinya kita masih saja gemar menjual moral, menggadaikan kebenaran, dan
bersembunyi di balik jargon-jargon suci paling beradab. Kita masih sibuk memuja
tokoh-tokoh baru yang ternyata hanya perpanjangan tangan dari kerakusan lama.
Di antara
puisi-puisi ini, kau akan menemukan ayah yang kehilangan rumah, ibu yang
menjual tubuhnya kepada penjajah, anak-anak yang menulis sejarah di atas tisu
pengelap toilet. Tapi jangan buru-buru menyalahkan tokohnya. Mereka adalah kita
semua. Republik ini adalah rumah tangga besar yang sudah terlalu lelah untuk pura-pura
bahagia.
Puisi-puisi dalam buku ini kuseret dari banyak
tempat: dari hutan yang ludes dibabat, dari pedalaman dan perbatasan, dari kota
yang isinya para alim ulama, dari kamar hotel tempat para politisi
menandatangani kontrak dosa dan kenikmatan sesaat. Aku menulis dari pengalaman
yang sebenarnya tak ingin kuceritakan, tapi harus kuterjemahkan agar kepalaku
sendiri jangan meledak.
Ohya buku ini tidak
hanya bisa dibaca. Ia juga bisa didengar. Setiap puisi kusulam ulang menjadi
lagu brutal. Aku merangkai nada dan suaranya dengan bantuan kecerdasan buatan (AI)
bukan untuk pamer teknologi, tapi untuk menguji batas: apakah mesin bisa diajar
untuk marah, bisa menjerit, menangis seperti manusia? Ternyata meski mesin dapat
belajar menggetarkan perasaan, tapi hanya homo sapiens yang bisa menanggung
maknanya. AI hanya alat; isi perutnya tetap kita.
Aku ingin pembaca pembaca
juga merasakan dentuman di dada. Itulah sebabnya aku memutuskan setiap puisi di
buku ini punya nyawa ganda: teks dan suara. Kamu bisa menelusuri QR code
di tiap halamannya, lalu mendengarkan versi musiknya yang cadas. Di situ, aku
dan mesin berkolaborasi menciptakan bunyi yang mungkin lebih jujur daripada
pidato seorang presiden mana pun di dunia.
Aku minta maaf
apabila musik yang lahir dari puisi-puisi ini tidak manis. Tidak mendayu-dayu.
Ia keras, mentah, hingar bingar, brutal, dan barangkali tak enak didengar. Tapi
justru di situlah kejujurannya, karena kehidupan negeri ini memang tidak sedang
indah bukan? Bahkan sebuah tagar di media sosial sempat viral dan membuncah. Suara
growl dan distorsi gitar yang
meledak-ledak adalah gema dari gelisah yang tak bisa diwakilkan lewat bahasa
yang santun dan sopan.
Mungkin akan ada yang
menuduh buku ini cabul, penuh kemarahan, hujatan dan makian. Tapi bagiku,
kata-kata hanya menjadi kotor ketika niat di baliknya kotor. Puisi-puisi ini
tidak lahir dari kebencian, melainkan dari cinta yang patah, cinta yang
dikhianati berkali-kali, dan cinta yang masih ingin percaya bahwa manusia bisa
lebih baik daripada sistem yang diciptakannya sendiri.
Aku menulis Republik
Kelamin di antara berita-berita kebohongan, di sela-sela kuliah, di sela rapat-rapat
yang membosankan, di tengah kemacetan dan doa yang diperdagangkan. Kadang di
meja redaksi, di studio musik, kadang di kamar hotel murah. Dan di setiap
tempat itu, aku melihat satu wajah yang sama: wajah bangsa yang lelah dan sakit
parah.
Jika setelah membaca
buku ini kamu merasa marah, kecewa, atau bahkan malu, berarti puisi-puisi ini telah
menuntaskan pekerjaannya. Sebab tugas puisi bukan menidurkan, bukan memberikan
solusi, tapi membangunkan nurani yang putus asa, memompa semangat berbangsa dan
bernegara kita yang nyaris punah.
Aku tidak tahu ke
mana buku ini akan pergi setelah dicetak kelak. Tapi kalau suatu hari nanti kau
membacanya dalam sunyi, lalu tiba-tiba mendengar dentuman drum dan raungan
gitar di kepalamu, jangan takut. Itu bukan musik dari luar. Itu suara dari
dalam dirimu sendiri, suara manusia yang lama bungkam tapi tak mau mengalah.
Selamat datang di Republik
Kelamin.
Negeri kata-kata yang lahir dari luka, tapi menolak mati.
— Wisnu Pamungkas
Yogyakarta, Desember 2025