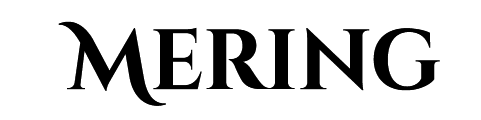Filsafat Dayak vs Filsafat Barat: Dua Cara Menjadi Manusia
 |
| Dayak mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan yang paling bebas, tapi yang paling selaras. |
Suatu sore—beberapa hari setelah peluncuran buku Filsafat
Dayak di Institut Teknologi Keling Kumang, Kalimantan Barat—sebuah nomor tak dikenal mengirim
pesan lewat WhatsApp.
“Bro, apa bedanya antara Filsafat Dayak dan Filsafat
Barat?”
Bukan hanya dia yang bertanya begitu. Beberapa kolega dan
kenalan dekat bahkan menelepon. “Bro, kenapa filsafat harus bawa-bawa suku
segala?” kata salah satunya sambil bercanda.
Tak hanya itu, mantan bos saya—yang kini tampangnya makin
mirip Plato—juga ikut penasaran. “Apa sih isi buku Filsafat Dayak itu?”
“Berarti Bos belum baca ya, hehehe,” jawab saya.
Sang mantan hanya nyengir kuda saat kami duduk santai di
sebuah kafe di kawasan Gejayan, Jogja. Ia lalu menyedot rokoknya dalam-dalam
sambil memandangi gerimis yang tak juga reda.
Buku yang ditulis oleh Prof. Tiwi Etika, Ph.D, bersama
sejumlah intelektual Dayak, memang telah mencuri perhatian banyak kalangan
dalam dua bulan terakhir. Buktinya, cetakan pertama langsung ludes. Minggu ini,
penerbitnya—Lembaga Literasi Dayak (LLD)—telah meluncurkan cetakan kedua,
lengkap dengan tambahan sekitar 112 halaman. Tebalnya kini menjadi 461 halaman!
Nah, kalau saya harus menjawab satu per satu pertanyaan di
atas, bisa gempor juga jempol ini tiap hari mengetik di keypad. Maka, kepada
Prof. Tiwi Etika, Ph.D, dan kelima sahabat penulis lainnya—Dr. Patricia Ganing,
Dr. Louis Ringah Kanyan, Dr. Wilson, M.Th, Masri Sareb Putra, M.A., dan
Albertus Imas, M.A.—izinkan saya, sebagai salah seorang inisiator penulisan
buku ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari sudut pandang saya yang
sederhana.
Sejak Plato mendirikan Akademia di bawah naungan pohon, di pinggir kota Athena, filsafat Barat tumbuh sebagai sistem berpikir yang menekankan
rasionalitas, logika, dan dikotomi antara tubuh dan jiwa, antara manusia dan
alam. Ia menjadikan pertanyaan sebagai alat tajam untuk menguliti realitas.
Namun jauh sebelum Descartes berkata, “Cogito, ergo sum”, masyarakat
Dayak telah hidup dalam filsafat yang tak tertulis—namun membentuk kehidupan
mereka secara menyeluruh: dalam hutan, dalam ritual, dalam nama-nama, dan dalam
tenun panjang yang diwariskan turun-temurun.
Filsafat Dayak bukan tentang perdebatan di ruang seminar. Ia
adalah cara hidup. Ia tidak mengandaikan dunia sebagai objek yang harus
dianalisis, dikendalikan, atau ditaklukkan. Bagi orang Dayak, dunia bukan “di
luar sana”. Dunia adalah “di dalam sini”. Hutan bukan sekadar latar ekologis,
melainkan makhluk dengan kepribadian dan kehendak. Manusia bukan pusat,
melainkan simpul dalam jejaring kehidupan.
Inilah perbedaan mendasarnya: filsafat Barat cenderung
antroposentris, sementara filsafat Dayak bersifat kosmosentris. Dalam pandangan
dunia Dayak, sungai, burung, batu, dan roh-roh leluhur memiliki eksistensi yang
sahih, sejajar dengan manusia. Bukan sekadar metafora, tetapi bagian dari
realitas relasional. Orang Dayak tidak hanya hidup di dalam dunia,
tetapi hidup bersama dunia.
Filsafat Barat berkembang melalui tulisan dan sistematisasi.
Filsafat Dayak hidup dalam cerita, adat, bunyi gong, dan gerak tari. Ia tidak
diajarkan lewat buku teks, tetapi melalui pengalaman bersama alam dan komunitas.
Ini bukan berarti filsafat Dayak “kurang rasional”, melainkan memiliki medium
dan bentuk epistemologi yang berbeda. Pengetahuan bukan hasil observasi netral,
tapi hasil relasi yang etis.
Satu contoh konkret adalah konsep tembawang—kawasan
hutan adat yang diwariskan dan dijaga lintas generasi. Tembawang bukan sekadar
wilayah pertanian berbasis agroforestri; ia juga adalah tempat suci tempat roh
leluhur bersemayam. Di dalamnya tersimpan bukan hanya sumber pangan, tetapi
juga sumber makna. Menebang pohon tanpa upacara adat atau tanpa izin dari Puyang
Gana bagi masyarakat Dayak Iban berarti mengganggu keseimbangan kosmik. Di
sinilah kita melihat bahwa dalam filsafat Dayak, etika tidak terpisah dari
ekologi. Sebaliknya, etika adalah ekologi.
Dalam filsafat Barat modern, manusia dianggap sebagai subjek
otonom, pemilik kehendak bebas dan rasio. Namun dalam filsafat Dayak, manusia
adalah bagian dari jaringan tanggung jawab. Kebebasan tidak dilihat sebagai
lepas dari keterikatan, tetapi sebagai kemampuan menjaga keseimbangan dalam
keterhubungan. Dengan kata lain, filsafat Dayak mengajarkan bahwa hidup yang
baik bukan yang paling bebas, tapi yang paling selaras.
Ketika kita bertanya, apa bedanya filsafat Dayak dan
filsafat Barat, kita seperti membandingkan air dengan api. Bukan soal mana
yang lebih unggul, tapi bagaimana keduanya memahami dunia dengan cara yang
sangat berbeda. Yang satu menyalakan obor untuk melihat lebih jelas, yang satu
lagi meresapi air untuk menyatu lebih dalam.
Mungkin inilah saatnya kita berhenti mengukur segala sesuatu
dengan parameter Barat. Filsafat Dayak tidak perlu dikodifikasi agar sah. Ia
sah karena hidup.
Yogyakarta, 9 Juli 2025