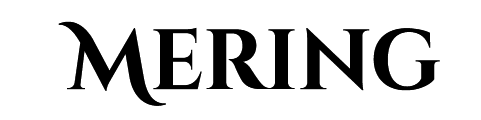Epilog Republik Kelamin: Renung dalam Kemarahan
Oleh: Zainal Abidin Suhaili (Abizai)[1]
|
S |
ajak tumbuh dan menjalar dari rasa, mimpi, harap, luka, kecewa, marah
dan sejarah seorang warga berbangsa dalam sebuah negara. Setiap manusia berhak
untuk menangkap dan kemudian meletuskankan himpunan rasanya lewat kata-kata.
Hal ini mungkin menyebabkan mengapa Wisnu Pamungkas menampilkan Kumpulan puisi Republik Kelamin seperti ini, berbeza daripada gaya
pengucapan lazimnya.
Puisi-puisi Wisnu
Pamungkas dalam
kumpulan ini tidak diraut dan dilengkungkan untuk meneduhkan rasa. Sebaliknya untuk mengusik, menyegat
dan menggugat, menelanjangkan mitos-mitos kebangsaan yang telah lama diterima
sebagai mantera kebenaran. Dalam puisi-puis ini, negara muncul melalui simbol
yang tidak lagi agung, malah hadir dalam bentuk tubuh, ranjang, iklan, skrin
monitor, hutan yang ditebang dan ingatan yang dipadamkan.
Puisi “Jakarta Bukan Tanah Air Beta” merakamkan sindiran yang tajam dan
sinis terhadap pusat kuasa yang
melahirkan mitos kebangsaan melalui bahasa rasmi, media, dan upacara politik. Penyair mempamerkan rupa
nasionalisme dalam bentuk propaganda, konsumsi, dan pengaburan sejarah. Tiada lagi berbekas wajah
asli cinta, empati dan jujur:
Jakarta
menciptakan mitos-mitos kebangsaan
menipu
orang-orang kampung yang sedang bingung
menjejalkan
sejarah tentang serdadu yang gagah perkasa
Jakarta
menciptakan mitos tentang apa saja
melahirkan
para penyamun dan kembang gula
ayah mengirim
SMS ke pada seorang kolega
"Jakarta
bukan tanah air beta!"
Letusan perasaan dalam sajak ini tidak dibiarkan menjadi liar. Ia dikawal melalui ironi, imejan tajam, dan
peralihan suara yang cermat. Menjadikan
kemarahan itu berfungsi sebagai renungan, bukan sebuah jeritan semata-mata.
Dalam puisi “Negara
Kelamin”, tubuh menjadi simbol
paling intim bagi negara. Hubungan suami isteri menjadi kiasan kepada medan kuasa, penaklukan dan pemecahan wilayah. Di
sini, Wisnu menjalarkan kebijaksanaan estetiknya. Persoalan politik
dan kebangsaan diturunkan ke ruang domestik, lalu dibesarkan semula sebagai
tragedi kolektif:
Tiada yang
salah pada hubungan mereka,
tapi ibu
mengira telah menjadi pahlawan
ketika
berhasil menyesah ayah di ranjang perkawinan
menciptakan
khayalan terhadap persetubuhan
menelan
lelaki itu mentah-mentah sebagai santapan
Ayah tiada
mengira kejantanannya bisa menjadi negara,
tetapi
akhirnya ia terpaksa berbagi wilayah dengan wanita itu
membuat
sempadan dari tirai,
membaca
proklamasi sendiri-sendiri di tapal batas
Perasaan
marah dan kecewa disalurkan melalui permainan bahasa, ironi kanak-kanak (“Hom pilahom pimpah!”) dan simbol yang mencemaskan. Berupaya menghasilkan kesan yang lebih tajam dan mendalam.
Puisi “Bayang Tembawang” mengalihkan renungan ke arah luka sejarah dan
kehilangan tanah adat. Puisi ini bergerak perlahan, penuh kesedihan yang
tertahan. Perkara ini menampakkan ketinggian penghayatan estetik Wisnu Pamungkas. Alam, mitos leluhur dan identiti komuniti
dipaparkan sebagai sesuatu yang dirampas oleh logik pasaran dan pembangunan:
Kemana ayah
akan pulang,
jika
tembawang musnah dicincang
menjadi
shampoo dan minyak peransang
dalam trolly
belanja selir-selir tersayang
Kemana ayah
akan pulang,
karena
kubur-kubur leluhur sudah jadi bubur,
menjelma mie
instant dan kaleng-kaleng biskuit
Tak ada yang
tersisa dari dongeng tentang enggang
padahal dulu
sayap dan paruhnya menyentuh langit
Kemarahan tidak mendadak meletus di sini. Ia tetap hidup membara dalam diam. Menjadi
sajak perang yang lahir daripada ketiadaan tempat untuk pulang.
Puisi “Virtualisasi Proklamasi Ayah” pula menjelma dalam nada ironis dan getir. Negara dilahirkan di hadapan
skrin, dibacakan seperti bil utiliti, dan dipimpin oleh presiden utopia yang
mengantuk:
ayah menekan beberapa
tombol, menghubungi rekannya
entah di
pulau mana, di laut, dalam hutan atau di angkasa
ayah membaca
teks proklamasi itu seperti membaca rekening
tagihan
listrik, ayah hanya mengenakan sarung saat
melahirkan
negaranya
yang
menyeruak bagai tunas di antara slogan-slogan
perdamaian
dan pucuk-pucuk senjata
ayah menguap
dari tempat duduknya:
apa boleh
buat ia sudah tercatat sebagai presiden utopia yang
Pertama
Penyair menyimpulkan bahawa dalam dunia kontemporari,
kemerdekaan dan kedaulatan telah terjerumus menjadi ritual kosong. Hanya sebuah
simulasi yang kehilangan makna sejatinya.
Republik Kelamin telah memenuhi syarat sebagai sebuah kumpulan puisi yang organik. Setiap puisi mampu berdiri kukuh sebagai karya tersendiri, namun
saling menyokong dalam membentuk wacana besar tentang warga, negara dan sejarah. Kesegaran gaya pengucapan, kedalaman renungan dan
kawalan emosi menjadikan puisi-puisi ini tidak berhenti di permukaan kemarahan sahaja. Ia meresap jauh
ke jalur pemikiran pembaca, menggugah alur perasaan, dan memaksa para pembaca menyoal kembali makna tanah air, negara dan diri.
Puisi-puisi Wisnu
Pamungkas tumbuh dan menjalar daripada getar rasa seorang warga yang enggan diam oleh tingkah rakus
penindasan. Ia menjadi wadah
untuk mengutuskan rasa itu dengan jujur dan berani. Membuktikan
bahawa kata-kata masih mampu menjadi medan perlawanan, renungan, dan harapan.