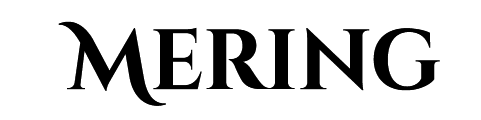Republik Kelamin: Sastra Terlibat - Sastra Hibrida - Puisi Bergerak
Oleh: Rudi Winarso
|
S |
etelah
beberapa kali mendengar dan membaca lirik puisi karya Wisnu
Pamungkas di buku kumpulan puisi “Republik Kelamin” ini membuat saya terlempar
di poros persimpangan arus jatidiri kebudayaan nusantara. Pusaran yang
mengerikan, arus liar tanpa irama bercampur hamburan sampah peradaban dari
berbagai benua dan samudra.
Jatidiri
nusantara mengalami tantangan yang besar di era digitalisasi dan globalisasi
pada abad ke-21 ini, di mana oligarki menyanggong
di persimpangan arus kuat peradaban besar dunia dari negara-negara pertama.
Tantangan untuk ikut arus atau semakin menguatkan keindonesiaan di tengah
perubahan besar yang diakibatkan oleh pelbagai perkembangan teknologi dan
terbentuknya tata dunia baru yang semakin terpolarisasi oleh peradaban besar
dan kepentingan oligarki menjadi wacana dan gerakan yang harus terus ditsunamikan oleh semua komponen
kebudayaan di negeri ini.
Pada
momentum ini, seorang Wisnu Pamungkas menemukan titik awal realita banalitas
tata kelola negeri ini, sebuah negeri yang sangat indah, tanah yang subur dan
melimpah, kekayaan laut yang melampaui harta karun, negeri yang rakyatnya
mempunyai hati yang sangat mulia, melebihi nilai gabungan semua batu mulia dan
logam mulia yang ada di seluruh bumi. Ironisnya, sebuah negeri yang melampaui
gambaran surgawi ini – dikelola oleh gerombolan bedebah.
Seorang
Wisnu Pamungkas dengan kelihaian menyusun kata-kata, huruf demi huruf mengalir,
meluncur dan menghantam bagaikan meriam kata-kata yang melumat anomali
kekuasaan.
Wisnu
menulis di kesunyian pedalaman awal mula peradaban Varuna-dvipa dan pinggiran
pantai Glagah-Adikarto, Wisnu menulis di keporakpandaan ibukota, pada intinya
Wisnu menulis di manapun dia berada sepanjang dia keliling nusantara maupun di
belahan benua manapun.
Wisnu
menulis tidak sendiri, dengan lihai dia merekrut gerombolan akal imitasi
kecerdasan buatan, mesin akal imitasi ini dirangkul dan dilatih menjadi
prajurit komposisi melodi dan harmoni sekaligus mesiu aransemen musik menjadi
kekuatan dengan daya ledak imaji indrawi untuk menghantam gerombolan bedebah,
dengan raungan kasar, tajam, berdebu kelam, gaduh silau bising, berisik dan
hingar bingar melalui pindaian kode respon cepat.
Saya
melihat Wisnu Pamungkas meracik kekuatan tulisan dan suara dalam buku kumpulan
puisi “Republik Kelamin” ini untuk meluluhlantakkan gerombolan bedebah dengan
tujuan membebaskan dan memuliakan rakyat negeri “surgawi”, dari puisi menjadi
“tsunami suara kata-kata”, bisa jadi ke depan menjadi “tsunami suara rupa
kata-kata”.
Menurut
saya, Wisnu Pamungkas dalam kumpulan puisinya menggunakan konsep sastra
terlibat—sebuah pendekatan yang merujuk pada pemikiran Jean-Paul Sartre.
Sastra, dalam pandangan ini, tidak netral: ia berpihak pada rakyat kecil,
menolak ketidakadilan, dan berani bersikap kritis terhadap realitas politik.
Gagasan
tersebut pernah diusung secara konsisten oleh Arief Budiman dan Ariel Heryanto,
serta menjadi polemik besar pada 1980-an. Arief Budiman, melalui esainya Sastra
yang Membebaskan, menegaskan bahwa sastra tidak cukup berhenti pada
permainan estetika, melainkan harus menjadi alat pembebasan dari penindasan
struktural. Ariel Heryanto bahkan menyatakan bahwa netralitas sastra dalam
rezim otoriter sejatinya adalah kompromi dengan kekuasaan.
Pada
2000-an, Sapardi Djoko Damono menawarkan gagasan puisi bergerak dengan
menuliskan puisinya di spakbor becak Malioboro—sebuah praktik yang memperluas
ruang hidup puisi. Dalam konteks ini, saya tidak melihat kelemahan berarti pada
buku Wisnu Pamungkas; kebaruannya terasa kuat.
Sebagai
tambahan, berikut beberapa contoh karya seni yang menjadi panggung kolaborasi
lintas disiplin—yang memungkinkan lahirnya “Wisnu-Wisnu” berikutnya.
Serat Centhini
Serat
Centhini, atau juga disebut Suluk Tambanglaras atau Suluk
Tambangraras-Amongraga, merupakan karya sastra kesusastraan Jawa Baru. Serat
Centhini menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa supaya
tidak punah dan tetap terlestarikan sepanjang waktu, atau disebut ensiklopedia
Jawa awal abad ke-18.
Serat
Centhini bukan sekadar buku biasa. Karya ini ibarat ensiklopedia kebudayaan
Jawa, memuat segudang pengetahuan tentang agama, kebatinan, dunia keris,
karawitan, tata cara membangun rumah, primbon, hingga cerita rakyat.
Kisahnya
mengikuti perjalanan putra-putri Sunan Giri yang berkelana menjelajahi Jawa,
mendalami adat, budaya, dan spiritualitas. Setiap baitnya penuh dengan renungan
filosofis yang menggugah kita untuk lebih memahami nilai-nilai kehidupan.
Babad Diponegoro
Pada
abad ke-19 Babad Diponegoro yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro
merupakan sebuah kritik tajam yang menelanjangi kebobrokan yang terjadi pada
masanya, baik di dalam tubuh Keraton Yogyakarta maupun pemerintahan kolonial Belanda.
Melalui
Babad Diponegoro, Pangeran Diponegoro tidak hanya menceritakan kisah hidup dan
perjuangannya, tetapi juga memberikan gambaran utuh tentang kondisi
sosial-politik yang tidak stabil dan penuh ketidakadilan pada awal abad ke-19
di Jawa, yang menjadi alasan utamanya melancarkan Perang Jawa.
Babad
Diponegoro menyoroti intervensi kolonial, kemerosotan moral elite, penindasan
rakyat, hingga pelanggaran nilai sakral budaya Jawa. Naskah ini tidak hanya
merekam perjuangan pribadi Diponegoro, tetapi juga potret ketidakadilan
sosial-politik Jawa abad ke-19, dan telah diakui UNESCO sebagai Memory of
the World.
Raden Saleh
Kontroversi
Raden Saleh terletak pada posisinya yang ambigu: bangsawan Jawa terdidik Eropa
yang melahirkan kritik kolonial lewat lukisan Penangkapan Pangeran
Diponegoro, namun juga bekerja dalam struktur kekuasaan Belanda. Lukisan
tersebut membalik narasi kolonial secara simbolik dan menjadi tonggak
nasionalisme visual Indonesia. Perdebatan tentang loyalitas, identitas, hingga
keaslian karyanya terus menyertainya hingga kini, sementara nisannya sendiri
mencantumkan gelar dari Raja Belanda, menimbulkan perdebatan apakah ia pahlawan
atau sekadar seniman oportunis.
Lukisan
"Penangkapan Pangeran Diponegoro" merupakan kritik terselubung: Lukisan
ini secara estetika membalik narasi Belanda, menempatkan Diponegoro di sisi
terhormat (kanan) dan penjajah di sisi kiri, menunjukkan pengkhianatan dan
perlawanan dengan simbolisme kuat.
The Tielman Brothers
The
Tielman Brothers adalah sebuah grup musik tertua asal Indonesia. Mereka adalah
anak dari Herman Tielman dan Flora Laurentine Hess asal kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur, yang memulai karir di Surabaya pada tahun 1947.
Grup
musik asal Indonesia ini merupakan pelopor genre Indo-Rock di Eropa.
Mereka dikenal lewat aksi panggung yang revolusioner, inovasi teknis instrumen,
serta sebagai band pertama yang merilis single
rock and roll di Belanda (1958). Pengaruh mereka bahkan disebut
menginspirasi musisi dunia seperti The Beatles dan Jimi Hendrix.
S. Sudjojono
"Jiwa
Ketok" adalah konsep seni S. Sudjojono, Bapak Seni Modern Indonesia, yang
berarti "jiwa yang tampak" atau "jiwa yang terlihat",
menekankan bahwa karya seni adalah perwujudan langsung dari jiwa dan isi hati
seniman, bukan sekadar keindahan teknis, melainkan ekspresi kebenaran dan
identitas diri serta bangsa, melawan seni Indie (Mooi-Indie) yang dianggap
dangkal.
Konsep
ini menganjurkan seniman untuk jujur pada perasaannya dan menyampaikan
kebenaran melalui karyanya, menjadikannya identitas seni Indonesia yang
autentik. Melalui konsep Jiwa Ketok, Sudjojono menegaskan bahwa seni
adalah manifestasi jiwa seniman—jujur, ekspresif, dan berpihak pada realitas.
Chairil Anwar
Dalam
masa revolusi, gagasan kebangsaan diwujudkan melalui kata dan visual
propaganda. Atas permintaan Bung Karno, Chairil Anwar berperan sebagai penulis
slogan, didukung S. Sudjojono dan Affandi. Poster legendaris “Bung, Ajo Boeng”
lahir dari semangat ini—terinspirasi bahkan dari bahasa sehari-hari kaum marginal
Jakarta.
Sastra
dan kebudayaan selalu bergerak dalam pusaran perubahan sosial, ekonomi, dan
politik global. Revolusi komunikasi membuat dunia kian terbuka—sekaligus
menjadi ancaman dan peluang bagi kebudayaan Nusantara. Di tengah pergeseran
kekuatan ekonomi dunia ke Asia, Indonesia berhadapan dengan arus modal besar
yang kerap melayani kepentingan oligarki.
Menariknya,
klaim budaya oleh negara lain justru memicu kebangkitan nasionalisme, seperti
gerakan batik yang berujung pada pengakuan UNESCO tahun 2009. Ke depan,
penguatan kebudayaan perlu terus diperbarui—bahkan dengan motif-motif
kontemporer yang merefleksikan realitas hari ini.
Namun
di tengah empati lintas bangsa atas bencana, sering kali yang terdengar dari
elite justru banalitas kekuasaan. Pada akhirnya, rakyat dipaksa tetap “sehat”
di tengah negara yang sedang sakit.
Maguwo, 19
Desember 2025
(77 tahun Agresi
II Militer Belanda; rakyat melawan dengan perang gerilya)