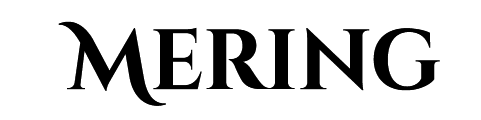Transmigrasi: Catatan dari Desa Warmon, Papua Barat
 |
| Ari Syamsudin Namugur. Dok Progrma Peduli-Kemitraan 2016 |
Tahun 2016 Aku berdiri di ujung desa, dekat komplek pemukiman (SP3). Udara panas menusuk. Di sebelah kiri, barisan gubuk berdiri rapat. Di sisi kanan, tanah lapang terbuka, bekas kebun lama. Di situlah aku bertemu Ari Syamsudin Namugur—Kepala Desa Warmon, Distrik Mayamuk, Papua Barat. Syamsudin berambut keriting, berkulit legam, dengan sorot mata yang tajam seperti sudah terlalu lama memendam kecewa.
“Luas
desa kami cuma dua hektare saja,” katanya tanpa basa-basi.
Aku
terdiam. Dua hektare? Tanah seluas itu tiada bedanya dengan luas kebun sawit satu
orang transmigran di Kalimantan Barat! Tapi Syamsudin tidak sedang bercanda.
Lahan itu diperoleh Syamsudin dan warganya (Suku Kokoda) berkat kebaikan MPM Muhammadiyah
Sorong.
Syamsudin masih kecil ketika
suara buldozer pertama kali memecah hening hutan leluhurnya. Ia menyaksikan
langsung bagaimana sagu yang dulu ditokok neneknya berubah menjadi batu bata,
atau bagaimana tanah ritual tempat para leluhur melakukan upacara adat
digantikan oleh jalanan lurus yang membawa para pendatang dari Jawa. Kini ia
mewarisi konsekuensinya.
“Tanah
kami digusur. Kalau protes, dianggap menolak pembangunan,” lanjutnya.
Kampung
ini berada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Cerita Syamsudin
adalah cermin Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan pulau-pulau lain di Indonesia.
Kisah tentang tanah yang tiba-tiba berubah status. Tentang peta yang digambar
dari atas meja pejabat negara, tanpa pernah menyapa orang-orang yang terdampak.
Aku
bertanya, “Kenapa bisa cuma dua hektare?”
Syamsudin
menunjuk ke arah pemukiman transmigran tak jauh dari situ. Rumah-rumah baru,
cat masih terang. Makmur sejahtera. Dulu, tanah itu tempat neneknya menokok
sagu. Tempat leluhurnya berburu rusa. Tempat upacara adat digelar saat bulan sedang
kembung sempurna.
“Sejak ada program SP3 transmigran.
Kami dianggap pendatang ilegal di sini. Padahal leluhur kami tinggal di sini jauh sebelum Indonesia diproklamasikan.”
Suara
Syamsudin rendah. Tapi nadanya menikam. Di matanya ada bola api yang menyala,
dibungkus kesabaran seorang kepala desa yang terlalu sering mengalah.
Entah
orang gila mana yang masih berpikir kalau Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan
pulau-pulau di nusantara ini adalah tanah kosong hari ini. Padahal disana ada tulang-tulang
leluhur kami, ada tempat-tempat keramat yang tersembunyi, ada jejak perburuan lama,
dan mata air purba di Tembawang yang kami rawat turun temurun.
Sejarah
transmigrasi di negeri ini sudah sanat panjang. Sejak zaman kolonial Belanda,
ide memindahkan penduduk dari Jawa ke luar pulau selalu diulang-ulang. Pada zaman
Orde Baru, lebih dari dua juta orang sudah dipindahkan dari Jawa dan Bali ke
pulau lain. Di atas kertas, ini terdengar mulia. Tapi program transmigrasi
itu telah menyebabkan kami semakin marah dan luka!
“Orang
luar datang diberi fasilitas bahkan sertifikat tanah. Tapi suku Kokoda justru terusir
dari tanah warisan leluhurnya,” kata Syamsudin pelan.
Aku
menelan ludah. Berat.
Hal
yang sama juga menimpa orang Dayak di Kalimantan. Mereka kehilangan
ruang hidupnya pelan-pelan. Baik akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, tambang
dan maupun program transmigrasi. Tapi yang membuatku tercekat pagi itu adalah
kenyataan bahwa desa Warmon Kokoda hanya
memiliki dua hektare tanah saja! Seluruh wilayah adat mereka
sudah lebih dulu dibagi-bagi rezim Orba kepada pendatang.
Cerita
Syamsudin bermain lama di kepalaku, hingga kemarin pemerintah mengumumkan 45
kawasan transmigrasi yang dijadikan fokus utama pembangunan nasional RPJMN
2025-2029 yang ditentang para demonstran, terutama di Kalimantan
Barat.
Saya
cemas suara-suara protes itu akan membentur senapan. Dituduh mengganggu
investasi dan tidak pro pembangunan. Sebab di era Orba dulu banyak aktivis yang hilang diculik. Padahal mereka hanya ingin hidup damai tanpa perselisihan.
Menjadi warga negara yang baik. Warga yang taat membayar pajak tanpa harus jadi maling!
Kisah
Suku Kokoda adalah kisah di banyak kampung di Indonesia. Baik di Papua maupun Kalimantan.
Dari pegunungan hingga ke pesisir paling pantai yang terpinggirkan. Sebuah kisah tentang
luka yang seakan sengaja diputar ulang. Tentang pembangunan yang kononnya adil tapi kurang beradab. Meski aku belum melakukan penelitian sendiri, tapi dari catatan sebagai jurnalis 20 tahun ini, aku hampir pasti: luka
transmigrasi terbaca jelas dalam tiga jejak, yaitu konflik agraria, kehancuran
lingkungan, dan peminggiran budaya masyarakat adat.
Aku menulis ini bukan karena sinis atau pun membenci. Tapi untuk mengingatkan bahwa pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke bukanlah tanah kosong. Dan suatu hari, ketika peta-peta dibuka dan rapat-rapat besar digelar, aku berharap ada satu kursi untuk orang seperti Ari Syamsudin Namugur disana. Agar ada yang berkata dengan lantang: “Kami tidak menolak pembangunan, Tapi janganlah anggap kami tidak ada di kalian punya republik!”