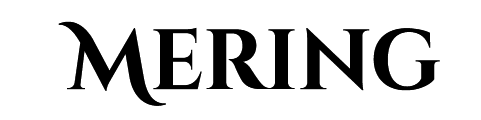Tembawang di Bawah Bulan
 |
| Illustration of Kerawing-Tembawang under the Moon by Mering with AI |
Cerpen: Wisnu Pamungkas
Namaku Kerawing. Nama yang artinya bintang—barangkali bintang yang bersinar paling terang di langit. Tapi aku tidak pernah melihat tembawang. Tidak pernah menyentuh tanah leluhurku di Pulau Dayak. Tidak tahu rasa gurih durian dari tanah itu, atau harum bunga bungkang (Syzygium polyanthum) yang mekar di bawah cahaya bulan. Tapi DNA-ku mengingatnya.
“Ayah,
aku ingin ke kampungmu,” kataku waktu SMA.
“Untuk
apa?” suara ayah berat.
“Aku
ingin melihat tembawang.”
Ayah
terdiam. Ia membuka laci tua, mengeluarkan album lama. Di sana ada foto: batang
pohon yang tinggi, burung enggang, anak-anak mencari buah durian, dan satu
potret lelaki gondrong duduk bersila di akar besar—menangis. “Itu aku, waktu
tembawang terakhir dibabat. Sejak hari itu aku menguburnya dari ingatan. Tak
ada batu nisan. Hanya karbon dan korban.”
“Apakah
tembawang itu hidup, Yah?”
“Barangkali
hanya di ingatan. Tapi jasadnya menghilang.”
Di
luar kamar ibuku diam. Malam itu, ia menyalakan dupa dan menabur bunga kantil
di pojok halaman. Katanya, itu “tempat teduh untuk roh yang terluka.” Ibu orang
Jawa. Ia tak pernah bicara keras. Tapi aku tahu: diam-diam hatinya menyimpan
banyak makam.
**
Aku
kuliah di ISI Jogja. Jurusan seni pertunjukan. Saat tugas KKN, aku ditempatkan
di sebuah kampung terpencil di Gunungkidul. Bukit karst, pohon jati, dan malam
yang tajam. Tempat dimana matahari selalu telat terbit dan paling cepat
terbenam. Satu-satunya yang terasa familiar hanyalah senyap.
Sampai malam itu, saat Brahmaraja datang. Seorang juru cerita keliling. Tubuhnya tinggi, berwajah tampan. Tapi matanya... seperti lubang hitam waktu. Di pertunjukan itu, ia menceritakan Dewa Ruci, tapi entah mengapa Bima bisa menjelma pohon, kepalanya menjadi durian, panggung berubah menjadi tanah. Entah karena bosan atau cerita Brahmaraja terlalu absurd, satu persatu penonton pulang. Hanya aku yang masih duduk di situ.
Setelah
usai, aku mendekat. “Juru cerita, ceritakanlah kepadaku tentang tembawang.”
Pria
itu menoleh. “Baiklah,” katanya.
**
Kami
duduk di bawah pohon jati.
“Apakah
kau tahu apa itu tembawang?” tanyanya.
“Dayak
Iban menyebutnya temawai, Dayak
Benuaq menyebutnya lembo, Dayak Nganju menyebutnya kaleka, Dayak
Jalai menyebutnya dahas, dan lain sebagainya. Para aktivis lingkungan menyebutnya
etno-agroforestry. Tapi bagiku tembawang bukan hanya itu. Ia adalah konsep yang
hidup bersama dan dalam diri orang Dayak, sebuah situs sekaligus ritus yang menghubungkan
manusia dengan semesta, dengan pengetahuan atau memori nenek moyangnya, dengan sumber energi, sang khalik
dan roh-roh.”
Brahmaraja
tersenyum. “Kau mengingatnya dengan baik, padahal belum pernah ke sana.”
“Entahlah,
ia ada dalam kepalaku.”
“Karena
kau bukan cuma manusia Kerawing. Kau adalah sebuah simpul. Darah Jawa dan
Dayak. Kau adalah buku yang belum selesai ditulis.”
**
Malamnya
aku bermimpi. Aku menari di tengah tanah lapang di tengah kampung. Tapi tubuhku
bukan tubuh, hanya jasad yang menyerupai tubuh tetapi sebenarnya bukan. Kakiku
menjalar menjadi akar. Pokok durian, cempedak, rambutan dan rotan tumbuh dari
jari-jari. Rambutku menjelma semak belukar. Ibu berdiri jauh, menyalakan dupa.
Ayah memotret bintang di langit. Brahmaraja berdiri di panggung yang perlahan-lahan
tenggelam.
“Aku
adalah tembawang. Apakah kamu bisa menghidupkanku,” tanyanya.
Saat
terbangun, tanganku berlumpur. Tubuhku basah berkeringat. Ada sebiji tengkawang
di bawah bantal.
**
Hari-hari
setelahnya, Brahmaraja muncul di mana-mana. Dalam bayangan, pantulan kaca,
bahkan dalam suara notifikasi ponsel.
“Kau
punya dua bahasa: Dayak dan Jawa. Dua tubuh. Dua akar. Jadikan tubuhmu
tembawang,” katanya.
Aku
mulai menggambar. Menari. AI visualnya berupa batik motif kawung dan pating melanjan
dibingkai gelung kelindan. Musiknya:
perpaduan suara gamelan dan irama sape’.
Gerakannya hibrida. Gentar dan ganjil.
Di
layar, Brahmaraja muncul lagi. Tapi kali ini ia tak bicara. Hanya mengangguk.
Orang-orang
menonton. Sebagian menangis. Sebagian melapor ke kepala desa ada pohon aneh
tumbuh di halaman rumah mereka.
Esoknya,
pohon jati tua di tengah-tengah kampung itu roboh tanpa angin. Di tempatnya, muncul
tunas kecil pucuk daunnya mirip tengkawang. Orang terheran-heran karena itu
bukanlah jenis pohon yang lazim tumbuh di tanah kapur.
**
Aku
membuat panggung dari tanah. Tak bicara. Tak bergerak. Tapi tubuhku mengalir.
Nafas jadi suara. Akar jadi isyarat. Seorang anak mendekat.
“Kak,
kamu manusia?”
Aku
ingin bilang ya. Tapi aku merasa aku adalah tembawang.
Setelah
itu, aku lenyap. Tapi di internet, muncul akun anonim bernama Tembawang. Isinya:
gambar-gambar pepohonan. Mulai dari pohon kemantan (Mangifera torquenda) hingga asam maram (Eleiodoxa). Dari buah durian hingga buah rukam (Flacourtia rukam). Sepasang macan dahan dan
orangutan mondar-mandir jadi carousel di
website. Kemudian muncul suara ricik air sungai, dan video Brahmaraja menyanyi
dalam bahasa dan kata-kata gaib.
Orang
menyebutnya karya seni. Tapi aku tahu itu bukan seni. Itu panggilan.
**
Suatu
malam, ayah menelepon. Suaranya gemetar. Ibu batuk-batuk di sampingnya.
“Kerawing...
aku mimpi kamu menari. Lalu kamu jadi pohon tapang (Koompassia excelsa). Dan aku... aku
menebangmu.”
“Hmmm.
Aku tidak marah kok, Yah”
“Kami
mencintaimu, Nak….”
Aku
tak menjawab. Ayah menutup telpon. Klik.
Kini,
setiap kali aku menarik napas panjang, bayangan Sirius—bintang paling terang di
langit—muncul di kepalaku berulang-ulang. Ia menyatu dengan roh tembawang, menari
dengan indah, mengepakan sayap seperti burung enggang, dan mengangkat paruhnya tinggi-tinggi,
menghisap seluruh oksigen yang tersisa di planet ini.
Jogja,
10 Juni 2025