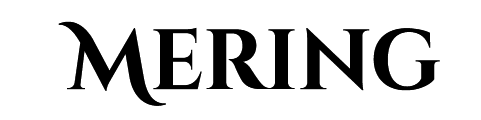Senja, Cuti, Malaria, dan Perusahaan Sendiri
 |
| Totok Setiawan |
Tiga bulan. Hampir tiga bulan, setiap pulang kerja, tak ada yang dapat aku lakukan di Pulau Gebe yang terpencil dan sunyi, selain menatap langit senja, perahu nelayan di kejauhan, kecipak ombak, dan air laut sore hari yang berubah seperti cairan tembaga kemerah-merahan tersepuh cahaya langit jingga, tersaput mega-mega.
Senja di Pulau Gebe
adalah senja yang memesona, lengkap dengan sebuah pantai yang pasirnya selalu
basah, gemerisik daun nyiur melambai serta siluet batu karang yang membuat kita
setiap waktu ingin duduk berlama-lama menyaksikan matahari terbenam,
perlahan-lahan melorot ke balik cakrawala.
Tapi apalah arti
keindahan senja di pulau terpencil untuk seorang pekerja tambang sepertiku.
Seorang lelaki yang jauh dari rumah, meninggalkan orang-orang tercinta,
meninggalkan keluarga dan menjadi orang asing di pulau yang hanya terdiri dari
air, waktu, debu tanah, dan senja. Tak ada telepon, tak ada senyum istri
tercinta, tak ada apa-apa di sini selain desau angin, raungan mesin, debur
ombak, dan senja yang selalu dipenuhi serangga.
Saat duduk di kantin sederhana
tempat orang-orang sering nongkrong setelah lelah seharian didera pekerjaan di
tambang, seorang teman tiba-tiba bertanya.
“Kapan terakhir dirimu
cuti?”
Aku melirik kalender
lusuh berdebu yang tergantung di dinding warung.
“Sudah berbulan-bulan
lamanya…,” jawabku tak berselera. Sebab supervisor sepertiku seharusnya dapat
jatah cuti dua bulan sekali. Tetapi karena tak beruntung, aku masih harus
mengantre. Konon kabarnya jatah cutiku baru akan dikabulkan oleh manajemen
beberapa minggu lagi. Buset!
Tiga bulan. Ya, sudah
hampir tiga bulan aku tidak pulang ke rumah kami di Bandung, Kota Kembang
tempat aku bertemu istriku dan kami membangun rumah. Entah bagaimana nasibnya,
yang saat kutinggalkan berangkat ke pulau ini dalam keadaan hamil, dan aku
tidak bisa menjadi suami siaga, tidak bisa mengantarnya ke Puskesmas.
Jauhnya jarak dan luasnya
samudra yang membentang menjadi portal tebal yang memisahkan kami berdua. Tak
terkatakan betapa berantakannya perasaan kami saat itu. Tapi apa hendak dikata,
aku sudah terlanjur memilih menjadi supervisor muda perusahaan kontraktor
tambang, di sebuah pulau terpencil di ujung timur Indonesia.
Dari udara Pulau Gebe
mirip senjata kujang yang sompel pinggir dan ujungnya. Luasnya sekitar 224 km²
saja, persis di ujung tenggara kaki Pulau Halmahera, berbatasan langsung dengan
Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Pulau yang ditumbuhi hutan mangrove dan
dipenuhi aroma kopra ini dulu adalah bagian dari wilayah kekuasaan Sultan
Tidore. Sebagian besar penduduknya beragama Islam berkat jasa Abdul Manau, dari
Palembang. Konon beliaulah yang mulai membangun permukiman hingga berkembang
menjadi Desa Sanafi. Seiring pertambahan penduduk, dan masuknya PT Aneka
Tambang (ANTAM) di Pulau Gebe tahun 1978, tumbuhlah desa-desa pemekaran yang
lain, seperti Desa Kacepi, Kapaleo, Mamin, dan Elfanun.
Aku baru mengetahui anak
pertamaku lahir, tiga bulan kemudian, saat diberi cuti oleh perusahaan.
***
Aku lahir di Sukabumi, 69
tahun silam, sebuah kota kecil di Jawa Barat yang terkenal dengan Pelabuhan
Ratunya. Belanda menyebutnya Wijnkoopsbaai yang berarti teluk anggur. Nama
tersebut menurut Profesor Veth berasal dari saudagar anggur zaman VOC bernama
Jan Jacobz. Di tempat itulah ayahku, Ukim Sasmita, sambil berdagang, selain
bertani seperti kebanyakan penduduk Sukabumi, dibantu oleh ibuku, Uum
Komariyah.
Seluruh masa kecilku
kuhabiskan di Sukabumi hingga tamat Sekolah Teknik Menengah Negeri (STMN) 1
Sukabumi. Orang-orang sering menyebutnya Kaboet 90. Entah dari mana asal-usul
julukan Kaboet 90 tersebut. Mungkin karena sering terjadi fenomena kabut tebal
di Sukabumi yang berada pada ketinggian 584 mdpl dan alamat sekolah kami persis
di Jl. Kabandungan No. 90.
“Untuk sukses, kamu harus
bekerja keras. Hiduplah jujur, tekun dan disiplin, serta jangan pernah meninggalkan
kewajiban ibadahmu kepada Tuhan Yang Maha Esa,” nasihat ayah suatu hari.
Tapi namanya juga masih
anak-anak, kata-kata ayah saat itu masuk telinga kiri dan keluar di telinga
kanan. Baru setelah aku tumbuh dewasa dan memasuki dunia kerja, barulah nasihat
ayah benar-benar kuhayati, dan bahkan sering terngiang-ngiang di kepala.
Nasihat ayahlah yang membuatku mampu bertahan, ketika kantor PT United Tractors
(UT), mengirimku ke Pulau Gebe untuk pertama kali. Sebuah keadaan yang
perbedaannya bagaikan langit dan bumi dengan Kota Bandung maupun Sukabumi.
Di dunia tambang, aku
memulai perjalanan karier di UT pada tahun 1975 sebagai Chief Operator
alat-alat berat. Lalu naik ke posisi Kepala Bagian Produksi, dan naik lagi
menjadi Project Manager 1987, sampai Operation Manager pada beberapa proyek
tambang PAMA. Pada tahun 2007, setelah 5 tahun menjabat sebagai PAMA Office,
aku mengakhiri masa baktiku di perusahaan Astra Group tersebut sebagai Presiden
Direktur PT Prima Multi Mineral (PMM), salah satu anak perusahaan PAMA.
Bersama teman-teman, kami
mendirikan PT Riung Mitra Lestari (RML) dan aku menjabat sebagai Vice President
Director hingga President Director. Terakhir aku menjabat sebagai Komisaris PT
Hasnur Riung Sinergy (HRS), yaitu sebuah perusahaan jasa kontraktor
pertambangan yang berpusat di Jl. Sudirman, Jakarta Selatan.
Keputusan mendirikan RML
tahun 2006 adalah sebuah tindakan berani jika tak mau dikatakan nekat.
“Siapa yang menginspirasi
Anda mendirikan perusahaan, setelah sekian lama hanya menjadi karyawan?” tanya
seorang kolega.
“Om William Soeryadjaya,”
jawabku mantap.
Suatu ketika William
Soeryadjaya (Tjia Kian Liong) berkunjung ke Balikpapan. Aku saat itu ditugaskan
membuat jalan perusahaan di Desa Sangatta, hingga hampir mati terserang
malaria. Meski menderita, ketika mendengar Om William bercerita bagaimana dia
berhasil merintis usahanya dari nol hingga sukses, semangat kami—terutama
aku—yang tengah kendor jadi bangkit kembali.
Dulu dia adalah anak
yatim piatu yang putus sekolah. Merintis usahanya dari bawah dan kita semua
tahu bahwa William Soeryadjaya kemudian berhasil mendirikan PT Astra
International (Astra), sebuah perusahaan besar di Indonesia.
Ketika bertugas di
Palangkaraya, hampir setiap tahun kami menghirup asap kebakaran hutan dan
lahan. Saat di Samarinda aku pernah kelaparan karena tak ada warung makan,
setelah menempuh perjalanan tiga hari tiga malam naik kapal kayu untuk menuju
tempat tugas. Pernah juga speedboat yang kami tumpangi mogok dan hanyut
terseret arus hingga ke Selat Makassar ketika menyeberangi laut.
Saat bertugas di
Kalimantan, kami harus berkendara selama tiga hari tiga malam menggunakan kapal
kayu ke hulu sungai dan masuk hutan. Transportasi belum lancar seperti
sekarang, berjalan kaki menuju tempat kerja bisa berjam-jam. Jika ada alat
berat perusahaan yang rusak maka kami harus memikul sendiri oli dan peralatan
ke hutan. Hidup berbulan-bulan di dalam tenda, mandi mencuci di sungai
langsung. Jangan berharap ada fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) di sana.
Berbeda sekali dengan saat ini di mana fasilitas sudah sangat baik.
Barulah ketika bertugas
di Belitung aku bisa pulang sebagai suami dan menemani istri saat melahirkan anak
kami yang ke-3. Bayangkan betapa sabarnya seorang wanita yang menjadi istriku.
Suatu ketika di tahun
2000, adalah hari yang berat karena tugas menghadapi pendemo di PT Adaro
Indonesia. Kami sekeluarga mendapat teror. Bahkan ancaman santet dan akan dibunuh.
Meskipun pada akhirnya semuanya dapat diselesaikan dengan baik, tetapi
peristiwa itu adalah saat-saat terberat bagiku selama bekerja di dunia tambang,
bahkan lebih berat dari ketika harus hidup di Pulau Gebe yang terpencil.
Pada saat aku masih
menjadi karyawan, ada sebuah kebiasaan yang sering kulakukan, yaitu selalu
menawarkan diri untuk membantu atasan atau bos. Dari situlah aku mendapatkan
pengalaman dan pengetahuan bagaimana mereka memimpin sebuah perusahaan.
Pada akhirnya aku ingin berbagi bahwa dunia tambang dapat menciptakan cukup banyak lapangan kerja sehingga dapat membantu bangsa dan negara tercinta. Inilah yang menyebabkan aku masih terus bekerja di dunia tambang.
*) Komisaris PT Hasnur Riung synergy dan owner PT Riung Mitra Lestari.
Cerita ini telah dipublikasikan di Buku 100 Anak Tambang Indonesia yang diterbitkan Allsysmedia, Bogor 2021